Kita Bicara Keberlanjutan, Tapi Mengapa Hal Kecil Masih Boros?
Hampir semua orang hari ini setuju bahwa keberlanjutan itu penting. Isu lingkungan sudah masuk ke ruang publik, dibicarakan di kampus, kantor, hingga media sosial. Mulai dari perubahan iklim, krisis air, sampai sampah plastik. Kesadarannya ada.
Masalahnya, kesadaran itu sering berhenti di level wacana.
Di kehidupan sehari-hari, kita masih akrab dengan lampu yang menyala di ruangan kosong, kran air yang dibiarkan mengalir, atau kebiasaan mencetak dokumen yang sebenarnya bisa dibaca di layar. Hal-hal kecil, nyaris tak terasa dampaknya, tapi terjadi berulang kali.
Ironisnya, banyak dari kita sebenarnya sudah tahu. Kita paham pentingnya hemat energi dan air. Kita mengerti bahwa sumber daya tidak tak terbatas. Namun, antara tahu dan bertindak, ada jarak yang tidak selalu mudah dijembatani.
Keberlanjutan sering dibayangkan sebagai sesuatu yang besar dan kompleks. Seolah harus dimulai dari kebijakan, teknologi mahal, atau perubahan sistem skala nasional. Padahal, persoalan besar justru ditopang oleh kebiasaan kecil yang terus direproduksi.
Tulisan ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah. Kita semua, termasuk penulis, masih berada di dalam lingkaran itu. Boros bukan selalu karena tidak peduli, tetapi karena sudah terlalu terbiasa.
Keberlanjutan pada akhirnya bukan soal menjadi paling benar, paling hijau, atau paling sadar lingkungan. Ia soal kesediaan untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah ini benar-benar perlu?
Jika pertanyaan sederhana itu mulai sering muncul sebelum kita menyalakan listrik, membuka kran, atau menekan tombol print, mungkin di situlah perubahan mulai bekerja. Pelan, tidak dramatis, tapi nyata.
Dan mungkin memang seperti itu cara keberlanjutan bertahan: bukan lewat slogan besar, melainkan lewat kebiasaan kecil yang konsisten.
Dalam Riset, Kedekatan Tidak Selalu Berarti Dukungan
Menyebarkan angket sering dianggap sebagai urusan teknis dalam penelitian. Buat instrumen, sebar tautan, tunggu respons. Selesai. Namun, di balik proses yang tampak sederhana itu, ada pengalaman emosional yang jarang dibicarakan.
Saya pernah berada pada situasi ketika harus meminta tolong teman dekat untuk membantu membagikan angket penelitian. Harapannya wajar: karena sudah saling mengenal, urusan berbagi tautan mestinya lebih mudah. Kenyataannya, respons yang datang justru biasa saja. Tidak diabaikan, tetapi juga tidak segera ditindaklanjuti. Kalimat “nanti ya” menjadi jawaban yang paling sering muncul.
Yang menarik, ketika angket yang sama dibagikan oleh rekan yang tidak terlalu dekat secara personal, respons justru lebih banyak. Tanpa sungkan, tanpa basa-basi. Angket diperlakukan sebagaimana mestinya: sebagai permintaan akademik yang perlu direspons.
Pengalaman ini perlahan menyadarkan saya bahwa kedekatan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan praktis. Teman dekat sering kali berada dalam situasi yang kompleks seperti kesibukan, rasa sungkan, atau asumsi bahwa permintaan tersebut tidak mendesak. Sebaliknya, relasi yang lebih berjarak justru memungkinkan sikap yang lebih profesional dan langsung.
Bukan berarti teman dekat tidak peduli. Justru sering kali karena kedekatan itulah muncul kelonggaran yang berujung pada penundaan. Di sisi lain, jarak menghadirkan kejelasan: apa yang diminta, dan apa yang perlu dilakukan.
Dari pengalaman sederhana ini, saya belajar satu hal penting dalam dunia akademik: kedekatan emosional bukan selalu modal dalam riset. Kadang, ia justru menghadirkan harapan yang terlalu tinggi. Dan belajar menurunkan ekspektasi adalah bagian dari kedewasaan sebagai peneliti.
Pada akhirnya, data tetap terkumpul, penelitian tetap berjalan, dan kita pun belajar memahami dinamika manusia dengan lebih jernih, termasuk diri kita sendiri.
Apakah Sains itu Netral?
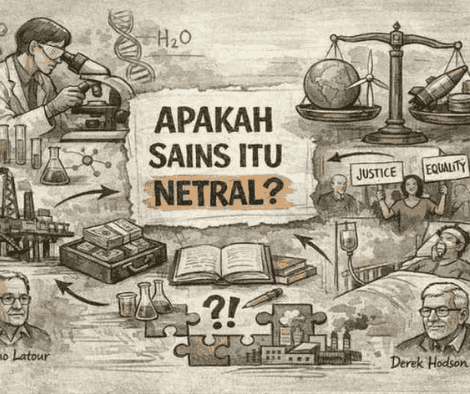
Pertanyaan “apakah sains itu netral?” terdengar sederhana, tetapi jawabannya justru membawa kita pada perdebatan panjang dalam filsafat ilmu, pendidikan, dan praktik riset modern. Selama bertahun-tahun, kita dibiasakan untuk memandang sains sebagai aktivitas objektif, bebas nilai, dan berdiri di atas fakta semata. Data adalah data. Angka adalah angka. Alam berbicara apa adanya, tanpa campur tangan manusia.
Namun, benarkah demikian?
Pandangan tentang netralitas sains berakar kuat pada tradisi positivisme dan rasionalisme modern. Dalam kerangka ini, sains dipahami sebagai upaya menemukan kebenaran objektif melalui metode yang ketat, terukur, dan dapat direplikasi. Bahkan pemikir seperti Max Weber pernah menekankan pentingnya value neutrality, bahwa ilmuwan seharusnya memisahkan fakta dari nilai agar pengetahuan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi atau ideologi.
Masalahnya, sains tidak pernah hidup di ruang hampa.
Pilihan topik penelitian, sumber pendanaan, metode yang digunakan, hingga bagaimana hasil riset diterapkan dalam kebijakan atau teknologi, semuanya melibatkan keputusan manusia. Dan setiap keputusan manusia selalu membawa nilai. Mengapa riset energi fosil jauh lebih masif daripada energi terbarukan selama puluhan tahun? Mengapa beberapa penyakit mendapat perhatian riset besar, sementara penyakit lain yang menimpa kelompok marjinal sering terabaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa sains bergerak dalam lanskap sosial, politik, dan ekonomi tertentu.
Di sinilah kritik terhadap mitos netralitas sains mulai menguat. Dalam pendidikan sains, Derek Hodson secara tegas mengingatkan bahwa mengajarkan sains seolah-olah bebas nilai justru berbahaya. Ketika mahasiswa hanya diajak menguasai konsep dan teknik, tanpa diajak merefleksikan dampak sosial dan etisnya, sains berisiko menjadi alat yang efisien, tetapi tidak bijaksana.
Lebih jauh lagi, pemikir seperti Bruno Latour menunjukkan bahwa fakta ilmiah tidak hanya “ditemukan”, tetapi juga dikonstruksi melalui jejaring laboratorium, instrumen, institusi, dan konsensus komunitas ilmiah. Ini bukan berarti sains fiktif atau sembarangan, melainkan menegaskan bahwa objektivitas sains selalu dicapai melalui proses sosial yang kompleks, bukan melalui kemurnian absolut.
Lalu, jika sains tidak sepenuhnya netral, apakah itu berarti sains menjadi tidak ilmiah?
Justru sebaliknya. Mengakui bahwa sains mengandung nilai adalah langkah menuju sains yang lebih bertanggung jawab. Netralitas bukan dihapus, tetapi diredefinisi. Objektivitas tidak lagi dipahami sebagai ketiadaan nilai, melainkan sebagai keterbukaan terhadap kritik, transparansi metode, dan kesadaran akan dampak sosial dari pengetahuan yang dihasilkan.
Dalam konteks pendidikan, pertanyaan “apakah sains itu netral?” seharusnya tidak dijawab dengan ya atau tidak secara hitam-putih. Pertanyaan ini lebih tepat dijadikan pintu refleksi: nilai apa yang sedang kita bawa ketika mengajarkan sains? Untuk siapa pengetahuan ini bekerja? Dan dampak apa yang mungkin muncul dari praktik ilmiah kita?
Di tengah krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial, sains yang berpura-pura netral justru berisiko abai. Sebaliknya, sains yang sadar nilai tanpa kehilangan ketelitian ilmiahnyadapat menjadi kekuatan transformasi. Bukan hanya membuat kita lebih pintar, tetapi juga lebih bertanggung jawab sebagai manusia.
Dan mungkin, di situlah tugas terbesar sains hari ini.
Belajar Sains Tidak Cukup Pintar, Harus Peduli !

Selama ini, belajar sains sering dimaknai sebagai proses menjadi pintar. Pintar memahami konsep, pintar menghafal rumus, pintar melakukan eksperimen, dan pintar menjawab soal ujian. Ukuran keberhasilan pun kerap berhenti pada angka: nilai, IPK, atau kelulusan tepat waktu. Namun, di tengah berbagai krisis lingkungan dan sosial yang kita hadapi hari ini, muncul pertanyaan penting: apakah kepintaran saja sudah cukup?
Sains memiliki peran besar dalam membentuk dunia modern. Teknologi berbasis sains membantu manusia hidup lebih sehat, lebih produktif, dan lebih nyaman. Tapi di saat yang sama, kita juga menyaksikan polusi, kerusakan lingkungan, krisis iklim, hingga ketimpangan sosial yang tidak sedikit bersumber dari penerapan ilmu pengetahuan yang minim refleksi. Ini menunjukkan satu hal penting: sains tidak pernah benar-benar netral.
Di ruang kelas, sains sering diajarkan seolah-olah terpisah dari kehidupan nyata. Mahasiswa sibuk mempelajari teori dan prosedur, tetapi jarang diajak berdiskusi tentang dampak dari pengetahuan yang mereka pelajari. Padahal, setiap pengetahuan ilmiah memiliki konsekuensi. Setiap teknologi membawa risiko. Setiap inovasi memunculkan pertanyaan etis. Jika aspek ini diabaikan, pendidikan sains berisiko melahirkan generasi yang cerdas secara teknis, tetapi kurang peka terhadap lingkungan dan masyarakat.
Pendidikan berkelanjutan hadir untuk mengingatkan bahwa tujuan belajar bukan sekadar menambah pengetahuan, melainkan membentuk kesadaran. Kesadaran bahwa sains digunakan untuk siapa, dengan cara apa, dan dengan dampak seperti apa. Organisasi seperti UNESCO menekankan bahwa pendidikan seharusnya membantu peserta didik berpikir kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada masa depan, bukan hanya mengejar capaian akademik jangka pendek.
Dalam konteks global, semangat ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals yang menempatkan pendidikan sebagai kunci transformasi sosial. Pendidikan tidak lagi cukup jika hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi abai terhadap persoalan lingkungan dan keadilan sosial. Dunia membutuhkan individu yang mampu mengaitkan pengetahuan dengan nilai dan kepedulian.
Peran pendidik sains menjadi sangat penting di sini. Cara dosen atau guru membingkai materi, memilih contoh kasus, dan membuka ruang diskusi akan menentukan bagaimana peserta didik memandang sains. Ketika sains diajarkan dengan konteks kehidupan nyata seperti banjir, limbah, energi, kesehatan, dan pangan. Mahasiswa belajar bahwa ilmu bukan sekadar alat intelektual, melainkan juga sarana tanggung jawab sosial.
Pada akhirnya, belajar sains memang penting untuk menjadi pintar. Tetapi kepintaran tanpa kepedulian justru berisiko melahirkan masalah baru. Pendidikan sains yang bermakna adalah pendidikan yang menumbuhkan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakan pengetahuan tersebut.
Ketika Pengetahuan Perlu Melangkah Lebih Dekat ke Kehidupan
Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi masyarakat saat ini. Di tengah krisis keberlanjutan—mulai dari persoalan lingkungan, akses sumber daya, hingga dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem kampus sering dipandang sebagai pusat lahirnya solusi berbasis pengetahuan. Namun, muncul pertanyaan reflektif: sejauh mana pengetahuan yang dihasilkan benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?
Banyak persoalan keberlanjutan tidak berdiri sendiri. Ia melibatkan dimensi teknis, sosial, ekonomi, dan budaya sekaligus. Karena itu, pendekatan berbasis pengetahuan tidak cukup jika hanya berhenti pada penguasaan konsep atau pengembangan teknologi. Diperlukan proses pembelajaran yang memungkinkan pengetahuan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Menjembatani Kampus dan Realitas Sosial.
Dalam praktiknya, dunia akademik dan realitas sosial sering berjalan dengan ritme yang berbeda. Kampus bekerja dengan logika riset, kurikulum, dan publikasi, sementara masyarakat berhadapan langsung dengan persoalan nyata yang menuntut solusi praktis dan kontekstual. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi perlu dijembatani. Pendidikan memiliki peran strategis dalam proses ini. Pembelajaran tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik memahami relevansi ilmu dalam konteks sosial dan lingkungan. Ketika pembelajaran mampu mengaitkan teori dengan realitas, lulusan perguruan tinggi akan lebih siap berkontribusi secara bermakna di luar ruang kelas.
Dari Pengetahuan ke Tindakan Bersama.
Pengetahuan memiliki nilai yang lebih besar ketika ia mampu menggerakkan tindakan. Oleh karena itu, hasil riset dan kajian akademik perlu diterjemahkan ke dalam proses belajar bersama yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai mitra yang ikut memahami dan mengembangkan solusi sesuai konteksnya. Proses semacam ini memang tidak selalu sederhana. Ia membutuhkan waktu, dialog, dan kesediaan untuk belajar satu sama lain. Namun justru melalui proses itulah keberlanjutan dapat tumbuh, karena solusi tidak hanya datang dari luar, tetapi dibangun bersama.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberlanjutan.
Upaya menjawab tantangan keberlanjutan menuntut kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Ketika kolaborasi berjalan dengan semangat saling belajar, pengetahuan dapat berfungsi sebagai bahasa bersama yang menyatukan berbagai kepentingan. Bagi dunia akademik, kolaborasi ini juga menjadi ruang refleksi: bagaimana pembelajaran dan riset dapat terus dikembangkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa kehilangan kualitas dan integritas ilmiahnya.
Pembelajaran sebagai Fondasi Masa Depan.
Keberlanjutan bukanlah hasil instan dari satu proyek atau satu kebijakan. Ia merupakan proses jangka panjang yang bertumpu pada pembelajaran yang terus berkembang. Dengan menempatkan pembelajaran sebagai inti strategi, perguruan tinggi berkontribusi pada pembangunan kapasitas masyarakat untuk merawat dan mengembangkan solusi secara mandiri.
Menuju Indonesia 2045, tantangan kita bukan sekadar menghasilkan pengetahuan, tetapi memastikan pengetahuan tersebut hidup dan bermakna dalam kehidupan sosial. Kampus memiliki peluang besar untuk menjadi ruang temu antara ilmu dan realitas ruang di mana pembelajaran tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memberdayakan.
